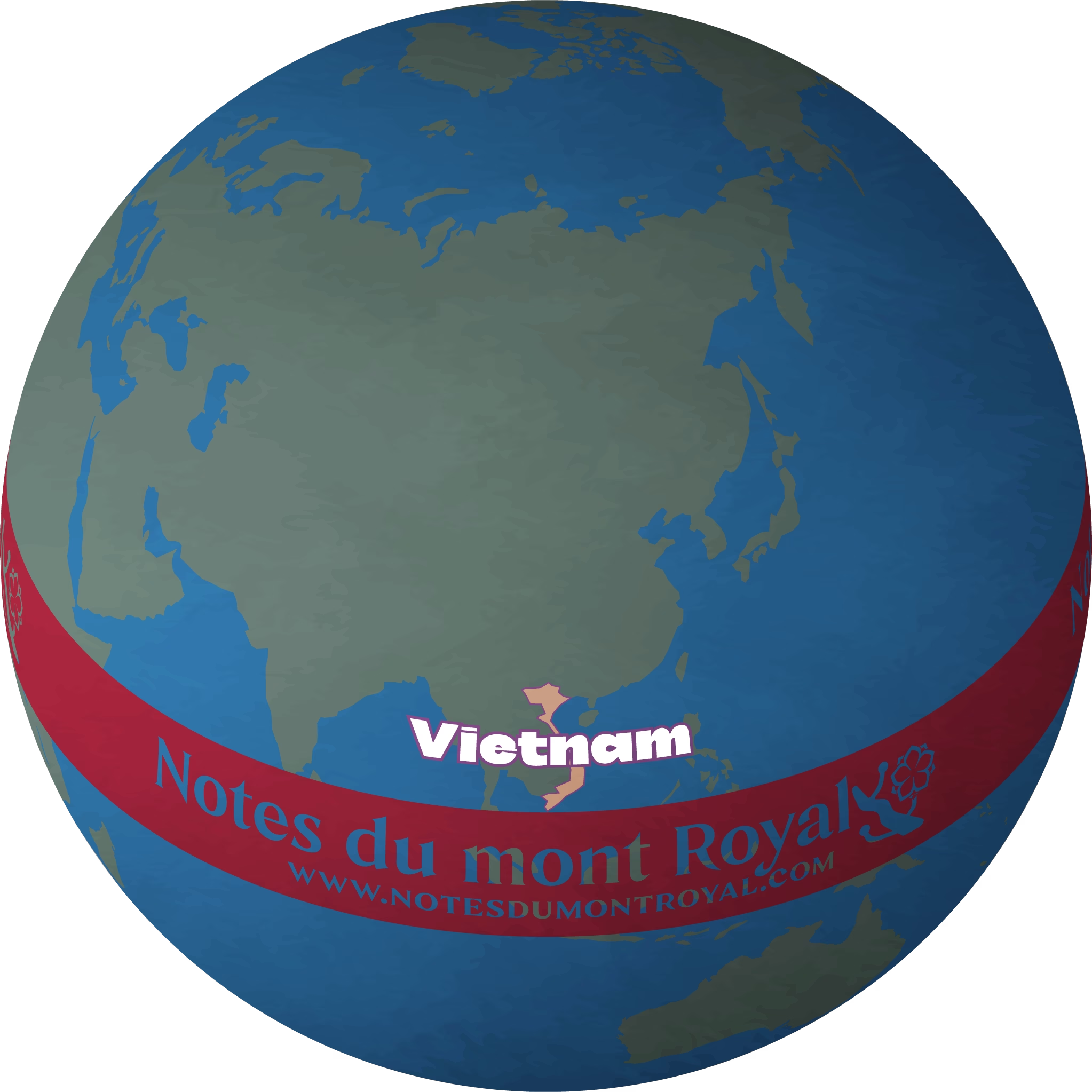Suara Rakyat yang Beragam: Nyanyian Chunhyang yang Setia
Diterjemahkan dari bahasa Prancis
Judul ini harus dipahami secara harfiah: Nyanyian Chunhyang (Chunhyangga)1Bentuk yang ditolak:
Le Dit de Chunhyang (Kisah Chunhyang).
Ch’un-hyang ka.
Choon Hyang Ga.
Čchunhjangga. adalah, pertama-tama, sebuah nyanyian. Untuk memahami esensinya, pejamkan mata dan bayangkan sebuah panggung kosong, yang dihuni oleh seorang penyanyi dengan kipas dan seorang penabuh gendang. Duo ini cukup untuk mewujudkan pansori, seni khas Korea yang oleh Serge Kaganski ditempatkan «di persimpangan antara teater, opera, pertunjukan, gospel, dan two-man-show». Gendang bergema dan suara serak meluncur, diiringi oleh kipas yang membuka dan menutup dengan bunyi tajam yang memberi tempo. Terbawa suasana, penonton bereaksi serempak, bagaikan «paduan suara Baptis», dalam persekutuan intens yang hampir menyerupai trance.
Lahir di atas panggung, nyanyian liris ini kemudian menjadi kisah dan berkelana, dibawa oleh tradisi lisan. Selama berabad-abad, segudang penulis anonim telah memperkayanya, menambahkan kisah-kisah lain tentang inspektur kerajaan dan cinta terlarang. Dari materi hidup ini akhirnya terendap, lapis demi lapis, teks-teks yang baku, edisi-edisi sastra acuan, yang paling terkenal adalah Kisah Chunhyang (Chunhyangjeon)2Bentuk yang ditolak:
Histoire de Tchoun Hyang (Kisah Tchoun Hyang).
Histoire de Tchyoun hyang (Kisah Tchyoun hyang).
Histoire de Tchun-hyang (Kisah Tchun-hyang).
Tchoun-Hyang-Djun.
Tchyoun hyang tjyen.
Tchun-Hyang Chòn.
Tchun-hyang djǒn.
Ch’unhyangdyǒn.
Ch’unhyangjǒn.
Choon Hyang Jun.
Choon-hyang-chon.
Choon Hyang Jon.
Chun-hyang-jon.
Ch’un-hyang Chǒn.
Chun-hyang-chun.
Chun-chyang-chun.
Czhun-hiang dzon.
Čchunhjangdžǒn., atau edisi gyeongpan, dan Nyanyian Chunhyang yang Setia (Yeolnyeo Chunhyang Sujeolga)3Bentuk yang ditolak:
L’Histoire de la constance de Chunhyang, femme fidèle (Kisah Kesetiaan Chunhyang, Wanita yang Setia).
Yol-nyo Ch’un-hyang Su-jeol Ga.
Yeolnye Chunhyang Sujeolga.
Yeollyeo-Chunhyang-Sujeolga., atau edisi wanpan.
Idyll Musim Semi
Kisah ini menceritakan cinta antara Chunhyang («Wangi Musim Semi»), putri seorang mantan penghibur, dan Mong-ryong («Mimpi Naga»)4Dalam beberapa sumber, alih-alih dengan nama depannya Mong-ryong, sang pahlawan disebut dengan sebutan Yi Doryeong. Bentuk ini menggabungkan nama keluarganya Yi dan gelar hormat doryeong yang diberikan kepada putra bangsawan yang belum menikah. Sebenarnya, ini hanya berarti «Tuan Muda Yi, Yi Muda».
Bentuk yang ditolak:
Ye Toh Ryung.
I-Toreng.
Ri To ryeng.
Lee Doryong., putra seorang gubernur bangsawan. Di Namwon, di provinsi Jeolla, saat bunga-bunga mulai bermekaran, pemuda terpelajar itu meninggalkan perpustakaan ayahnya untuk berjalan-jalan di alam terbuka. Di sana, ia melihat Chunhyang sedang bermain ayunan. Pertemuan pertama ini dilukiskan dengan kehalusan cetakan kayu yang paling indah:
«Ia menggenggam tali dengan tangan lembutnya, naik ke papan dan terbang. […] Dedaunan pohon mengiringi ayunannya maju-mundur. Merahnya rok membuatnya tampak sebagai titik bahagia di atas hijaunya pepohonan. […] Dilihat dari depan, ia bagaikan burung walet yang menukik untuk menangkap kelopak bunga persik yang meluncur ke tanah. Dari belakang, ia tampak bagai kupu-kupu warna-warni yang menjauh mencari pasangannya.»
Le Chant de la fidèle Chunhyang (Nyanyian Chunhyang yang Setia), diterjemahkan dari bahasa Korea oleh Choi Mikyung dan Jean-Noël Juttet, Cadeilhan: Zulma, 1999; cetak ulang Paris; Veules-les-Roses: Zulma, koleksi «Z/a», 2025.
Cinta, menyambar dan seketika, mendorong pemuda bangsawan itu untuk menentang konvensi. Ia mengunjunginya di malam hari. Begitu melewati ambang kamar, gadis rakyat jelata ini ternyata tak kalah terdidik dan berbudaya darinya: pandangan menyapu puisi-puisi tulisan tangannya yang tergantung di atas meja kerjanya, kaligrafi, lukisan. Di tengah dekorasi inilah para kekasih bertukar janji, mengukuhkan ikatan yang masih mereka rahasiakan, terpisah oleh kelahiran dan kekayaan.
Ujian Kesetiaan
Pada saat itu, ayah Mong-ryong dipanggil kembali ke Hanyang (Seoul); sang pemuda harus mengikutinya untuk menyelesaikan studinya dan mengikuti ujian mandarin. Ia meninggalkan di belakangnya seorang istri yang mencinta dan setia yang, bagaikan Penelope baru menunggu kepulangan Odysseus-nya, bersumpah untuk menghormati «janji yang seribu kali lebih berharga dari emas, seribu kali lebih indah dari batu giok».
Drama terjalin dengan kedatangan pengganti di posisi gubernur, Byun Hak-do, seorang pria penuh nafsu dan kejam. Setelah mendengar tentang kecantikan Chunhyang, ia menuntut agar gadis itu melayaninya. Pengambilan absen para kisaeng digambarkan dengan kelucuan ala Rabelais, di mana nama-nama yang menggugah berdefile, seperti Nona «Kabut Misterius», «Bunga Aprikot» atau «Peri Sungai». Hanya Chunhyang yang tidak hadir. Diseret ke hadapan sang tiran, ia berani melawannya, berargumen bahwa seorang wanita berbudi tidak dapat melayani dua suami, meskipun ia berasal dari kelas rendah:
«Apakah kebajikan, kesetiaan ada hubungannya dengan status sosial?»
Le Chant de la fidèle Chunhyang (Nyanyian Chunhyang yang Setia), diterjemahkan dari bahasa Korea oleh Choi Mikyung dan Jean-Noël Juttet, Cadeilhan: Zulma, 1999; cetak ulang Paris; Veules-les-Roses: Zulma, koleksi «Z/a», 2025.
Atas keberanian ini, ia menjalani siksaan. Setiap cambukan yang menghantamnya menjadi kesempatan untuk menyanyikan lagu perlawanan, litani menyakitkan di mana ia menegaskan kembali kesetiaannya. «Bahkan jika aku dibunuh sepuluh ribu kali», serunya, «cinta yang bersemayam di hatiku, cinta yang mengikat enam ribu sendi tubuhku, cinta ini tidak akan berubah.»
Saya tidak akan menceritakan akhir ceritanya, kecuali bahwa ia bahagia.
Balas Dendam Hati Melawan Kekejaman Kesewenang-wenangan
Nyanyian Chunhyang yang Setia mencakup seluruh tangga sosial Zaman Kuno, dari yang tertinggi untuk Mong-ryong hingga yang terendah untuk Chunhyang. Keberhasilannya terletak pada kenyataan bahwa «ia berani berbicara terang-terangan tentang cinta di negeri di mana hati-hati muda tercekik di bawah otoritas» dan di mana pernikahan, urusan akal sehat, ditangani dengan dingin tanpa mereka punya suara. Tuntutan pribadi ini dilengkapi dengan kecaman politik terhadap penyalahgunaan dan korupsi yang merajalela di kalangan penguasa.
Memang, saya akui, kisah ini kadang menderita dari berbagai tambahan yang ditimbulkannya; Bulletin critique du livre en français mencatat di dalamnya «beberapa ketidakkonsistenan, pembenaran yang kikuk, […] kenaifan dan sentimentalitas». Namun, seperti kerang yang mengembalikan deru samudra, ia menyimpan, di balik semua itu, «bisikan dan seperti dengungan besar yang redup: suara besar yang tak terbatas dan beragam» dari para penyair rakyat yang bernyanyi di sekelilingnya5Mengutip Hippolyte Taine dan Philosophie de l’art (Filsafat Seni)-nya yang agung.. Jiwa mereka yang bergetar, perasaan mereka yang baik dan murni telah membawa karya ini melewati berabad-abad; mereka masih menghidupkannya hari ini, selama festival besar Namwon, di mana para myeongchang (penyanyi ulung) terbaik bersaing. Lee Mee-Jeong melaporkan bahwa beberapa di antara mereka berlatih dengan begitu gigih «untuk memberikan suara mereka kesempurnaan ekspresi sehingga mereka sampai memuntahkan darah». Pengorbanan mereka sama sekali tidak sia-sia, disaluti oleh penonton yang berdiri untuk bertepuk tangan, dengan air mata berlinang. Dan «air mata penonton kontemporer ini sama mengharukan dengan penderitaan dan reuni para kekasih dalam fiksi».